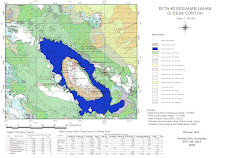30 Juli 2008
PENGELOLAAN HUTAN SKALA KECIL : Perubahan Skala Pengusahaan Hutan dan Partisipasi Masyarakat
A. Pendahuluan
Selama dua dekade terakhir, terlihat kecenderungan bergesernya fokus industri kehutanan dari industri skala besar ke arah pengelolaan hutan skala kecil (PHSK) berbasis masyarakat. Kecenderungan ini terutama terlihat di negara berkembang dimana industri pembalakan komersial skala besar untuk memenuhi permintaan kayu yang tidak lestari mulai bergeser ke arah manajemen hutan skala kecil dengan manfaat ganda yang dapat menopang kehidupan masyarakat. Di Eropa dan Amerika, pergeseran PHSK dimulai dengan berkembang pesatnya demokratisasi yang membawa implikasi terbaginya lahan negara menjadi lahan milik pribadi.
Definisi dan konsep PHSK berbeda antar masing-masing negara. Sebagai contoh, di India PHSK memiliki areal kurang dari 1 ha. Istilah PHSK yang dipraktekkan di Eropa dengan luas 25-40 ha, tidak sama dengan Amerika Serikat yang memiliki lahan yang luas (rata-rata lebih dari 40 ha), atau di Jepang, dimana kebanyakan pengelolaan hutan memiliki skala mikro (1-5 ha).
Di banyak negara berkembang, PHSK lebih berkaitan dengan kehutanan masyarakat dibandingkan dengan industri kehutanan skala besar serta dilakukan pada hutan negara sebagai praktek pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Walaupun PHSK juga melibatkan pengelolaan areal hutan yang relatif luas (dapat lebih dari 100 ha) secara komunal, tetapi areal tersebut masih relatif kecil dibandingkan industri kehutanan skala besar, misalnya HPH dan HTI dengan luasan lebih dari 10.000 ha).
B. Pengelolaan Hutan Skala Kecil di Beberapa Negara
Praktek PHSK relatif berbeda di berbagai negara. Dengan Small Forest Certification, tidak kurang 425.000 orang pemilik hutan terorganisasi dalam serikat-serikat kecil pengelolaan hutan di Kanada. Sebagian besar kawasan hutan tersebut terpisah dalam luasan-luasan kecil. Kondisi yang serupa terdapat di Jepang. Hutan skala kecil mendominasi kepemilikan lahan hutan yang ada (57,9%), sehingga produksi kayu Jepang sebagian besar (76%) berasal dari lahan hutan pribadi. Sebagian besar hutan milik tersebut memiliki luasan kecil (90% memiliki luas < 2 ha), sisanya dimiliki perusahaan kehutanan dengan rata-rata luas 34,6 ha, dan kelompok masyarakat dengan luas rata-rata 19,3 ha. Di Amerika Serikat terdapat sekitar 600.000 pemilik hutan dengan luas minimal 40 ha yang menghasilkan 80 % total produksi kayu nasional.
Negara-negara Eropa, misalnya Finlandia lebih dari 600.000 keluarga mengontrol 60% kawasan hutan di negara tersebut. Di Swedia dan Norwegia pemilik hutan merupakan keluarga yang telah mengelola hutan secara tradisi dengan luasan 25-40 ha. Sedangkan di Jerman, Austria dan Swiss; umumnya pemilik hutan mempunyai luasan kurang dari 5 ha. Satu hal yang perlu dicatat bahwa pada umumnya praktek PHSK pada negara-negara di atas lebih berbentuk hutan tanaman.
C. Pengelolaan Hutan Skala Kecil di Indonesia
Fragmentasi hutan memperlihatkan kenyataan bahwa sangat sulit membuat sebuah unit manajemen utuh dan kompak dengan tegakan hutan yang luas terutama pada hutan produksi. Tegakan-tegakan yang ada, umumnya berada dalam luasan kecil sampai ratusan hektar bahkan mungkin hanya puluhan hektar saja. Di sisi lain, kebutuhan kayu dan lahan semakin meningkat sedangkan suplai kayu dari hutan alam semakin menurun akibat degradasi hutan yang luar biasa yang disebabkan kesalahan pengelolaan hutan.
Praktek pengelolaan hutan dalam luasan yang kecil sebenarnya telah ada sejak lama di Indonesia. Sebagai contoh, sebuah keluarga di Jawa misalnya dapat memiliki hutan jati atau sengon dengan luas puluhan hektar, yang disebut ”hutan keluarga”. Hutan milik tersebut tidak selalu berupa satu kesatuan tetapi dapat terpisah-pisah, bahkan hanya berupa tegakan pembatas tanah. Di Bali hutan sengon yang dikelola masyarakat berkembang untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kayu untuk industri kerajinan patung. Dalam perkembangannya hutan-hutan yang demikian disebut juga hutan rakyat.
Dari hasil Sensus Pertanian 2003 menunjukkan di Indonesia tercatat sekitar 1,2 juta rumah tangga yang mengusai tanaman akasia dengan populasi mencapai 32,02 juta pohon atau rata-rata penguasaan 27,24 pohon per rumah tangga. Sekitar 12,06 juta pohon atau 37,69 % diantaranya adalah merupakan tanaman akasia yang siap tebang.
Beberapa contoh praktek PHSK yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia lainnya adalah repong damar di Pesisir Krui Lampung, Tembawang di Kalimantan Barat; Lembo di Kalimantan Timur dan sebagainya dengan hasil hutan non kayu sebagai produk utamanya.
Skala unit pengelolaan yang kecil memungkinkan modal yang dibutuhkan lebih sedikit dibanding industri kehutanan skala besar, padat karya sehingga memberikan fleksibilitas mengubah pola sasaran produksi dan manajemen sebagai respon terhadap fluktuasi harga, serta sensitifitasnya terhadap permasalahan dan peluang yang dihadapi. Fleksibilitas tersebut dapat tercermin pada rezim penebangan yang dipilih yakni penebangan dilakukan pada saat yang tepat yakni ketika harga jual kayu sedang tinggi. Tegakan hutan tersebut dapat sebagai tabungan yang ditebang pada saat dibutuhkan, misalnya membiayai pesta perkawinan anak, uang sekolah anak dan sebagainya.
Akan tetapi beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan dalam mengelola hutan skala kecil seperti (1) ukuran luas minimal, (2) teknik pengaturan hasil, (3) teknik pemanenan dan pemasaran hasil belum sepenuhnya diketahui. Banyak hal yang mengakibatkan hal tersebut belum dapat dikuasai. Orientasi industri kehutanan skala besar dan negara merupakan superordinat masyarakat dalam pengelolaan hutan merupakan beberapa penyebab belum berkembangnya PHSK di Indonesia.
Ketidakpastian kawasan hutan akibat masalah tenurial tidak jelas, susahnya memasarkan produk kayu akibat kalah bersaing dengan rendahnya harga kayu dari penebangan liar (illegal logging) dan sulitnya mengeluarkan sertifikasi produk kayu dari PHSK mengakibatkan banyak usaha PHSK yang telah dirintis kembali tenggelam.
D. Pengembangan Strategi Pengelolaan
Merujuk makna “skala kecil berbasis masyarakat” adalah proses pergeseran paradigma kehutanan, perubahan sikap dan orientasi, mekanisme institusional, dan metode manajemen maka yang hal yang perlu dipersiapkan adalah :
1. Kepastian kawasan dan distribusi lahan hutan.
Kepastian wilayah kelola berkaitan dengan akses masyarakat terutama pada kawasan yang saat ini dinyatakan sebagai hutan negara. Kepastian wilayah kelola yang dimaksud bukan membagi-bagikan kepemilikan lahan tapi lebih pada kepastian akses pengelolaan jangka panjang.
Sistem Plasma dan Inti
Sistem ini meniru prinsip inti – plasma pada perkebunan, di mana petani-petani kecil mengelola perkebunan dalam skala kecil dan bergabung dalam suatu serikat untuk menjual produk perkebunannya. Pada umumnya petani-petani kebun ini dibina oleh sebuah perusahaan perkebunan besar dan sekaligus menampung produk petani kecil tersebut. Prinsip ini berpeluang untuk diterapkan pada PHSK. Pemerintah atau BUMN dapat menjadi inti yang bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pembelian produk-produk dari hutan skala kecil.
Dalam prakteknya, sistem inti – plasma ini telah mulai diterapkan pada pengelolaan HTI PT. Toba Pulp Lestari di Sumatera Utara. Perusahaan bertindak sebagai inti yang menyediakan sarana produksi dan bimbingan teknis, masyarakat sebagai plasma menyediakan lahan dan tenaga kerja. Masyarakat memperoleh pendapatan dari upah pembangunan hutan tanaman dan persentase harga jual kayu kepada perusahaan. Mekanisme penentuan harga dan persentase bagian masyarakat ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara perusahaan dan petani yang dimediasi pemerintah daerah. Skim ini terbukti dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sebesar Rp 575 ribu per ha per tahun atau Rp 7,3 juta per tahun atau kurang lebih Rp 58,6 juta dalam satu daur 8 tahun dengan luasan andil rata-rata 12,75 ha. Kolaborasi ini telah mengurangi terjadinya sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan.
2. Kelembagaan unit usaha dan kepastian unit usaha sebagai bentuk pengelolaan.
Kelembagaan unit usaha sangat penting sebagai alat bahwa PHSK memiliki aturan main yang jelas dan mekanisme pertanggung-jawaban atas hak kelola yang diberikan. Kejelasan tata kelola hak, kewajiban dan tanggung-jawab serta insentif dalam pengelolaan sumberdaya menjadi dasar pengembangan kapasitas kelembagaan unit usaha pengelolaan hutan.
Kepastian unit usaha berkaitan dengan skim ekonomi dimana modal, akses informasi pasar, pengembangan komoditi, dan pengetahuan lokal menjadi substansi dasar PHSK. Kepastian unit usaha dapat digunakan sebagai mandat usaha ekonomi yang layak dan memberikan kepastian hasil dan peningkatan ekonomi masyarakat. Banyak contoh kasus kurangnya akses informasi terhadap harga mengakibatkan kayu dari hutan skala kecil (hutan rakyat) dihargai rendah sehingga menjadi disinsentif bagi masyarakat dalam mengelola hutannya.
3. Peningkatan kapasitas manajerial dan teknik.
Dalam pengembangan PHSK, sumberdaya manusia pengelola dan pendamping teknis menjadi kebutuhan penting. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia adalah prasyarat mutlak karena PHSK tidak lagi hanya untuk memenuhi kebutuhan subsisten masyarakat tetapi lebih besar pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pada banyak kegiatan pengembangan kehutanan masyarakat, rendahnya kemampuan teknik dan manajerial, termasuk strategi pemasaran produk dan pemilihan jenis telah mengakibatkan kegagalan. Oleh karena itu diperlukan pengembangan kapasitas masyarakat terutama dalam menyerap teknik pengelolaan sumberdaya yang sederhana dan tepat. Peningkatan teknik pengolahan hasil juga dapat memberikan peningkatan nilai tambah lokal, sehingga masyarakat dapat menerima manfaat yang lebih besar dari sumberdaya hutan yang mereka kelola.
4. Perencanaan pengelolaan sumberdaya hutan secara akurat.
Sekurangnya unsur-unsur perencanaan paling sedikit memuat : (a) data dasar potensi hutan, keadaan sosial ekonomi masyarakat melalui inventarisasi yang akurat, (b) tujuan dan sasaran pengusahaan yang jelas, (c) memiliki program yang jelas, (d) dukungan kelembagaan dan pendanaan, dan (e) monitoring dan evaluasi.
Perencanaan tersebut harus melalui proses yang partisipatif dengan melibatkan semua komponen masyarakat. Tahap kritis dalam perencanaan pembangunan hutan skala kecil adalah seberapa luas hutan skala kecil yang akan ditanami setiap tahunnya. Pertanyaan ini akan menentukan keputusan pertimbangan anggaran, praktek pengelolaan hutan, perencanaan lingkungan dan perencanaan pengembangan pembiayaan dan pendapatan.
Pemilihan jenis yang tepat merupakan pertimbangan penting dalam mengelola hutan dengan luasan yang kecil. Pemilihan jenis yang memiliki nilai ekonomis tinggi akan mereduksi besaran biaya tetap per meter kubiknya. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan, penanaman tanaman pokok dapat diselingi dengan tanaman pertanian dan tanaman berdaur pendek lainnya dengan sistem tumpang sari maupun agroforestry. Selain memberikan tambahan penghasilan, sistem ini juga mendukung keberhasilan tanaman pokok yang ditanam.
5. Pemasaran hasil hutan
Pada banyak kasus, pemasaran hasil hutan merupakan faktor penting dalam pengembangan PHSK. Harga kayu yang rendah dan tidak adanya pasar yang menampung kayu masyarakat tersebut mengakibatkan banyak program PHSK tidak berjalan dengan baik. Dengan pola inti – plasma atau perserikatan, plasma dapat memasarkan kayu yang mereka panen kepada inti atau perserikatan tersebut. Adanya posisi tawar yang baik akan mendorong terciptanya tingkat harga yang adil.
6. Mekanisme penyelesaian sengketa
Mekanisme penyelesaian sengketa lahan dan sosial (terutama pada lahan negara) dalam memberikan kepastian hak pengelolaan dan unit usaha kelola. Penyelesaiakan sengketa yang berkaitan dengan akses masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya dapat dijadikan instrumen untuk melakukan tahapan pergeseran perubahan sikap dan orientasi, serta mekanisme institusional dan administratif.
7. Kebijakan yang mendorong dan insentif pengelolaan jangka panjang.
Rendahnya permodalan yang dimiliki petani harus diatasi dengan pemberian insentif dan subsidi oleh pemerintah kepada pemilik/pengelola hutan. Bantuan dapat berupa subsidi keuangan, dukungan teknis, dan tenaga pedamping. Di Jepang, PHSK mendapat subsidi 68 % dari biaya penanaman dan penjarangan non komersial dari pemerintah berdasarkan Basic Forestry Law tahun 1964. Selain itu setiap tahun pemerintah menyediakan dana untuk pendukung pembangunan sarana jalan dan mesin-mesin untuk memajukan kawasan perdesaan.
8. Monitoring, dan evaluasi
Monitoring dan evaluasi dikerjakan oleh pemerintah dan oleh masyarakat sendiri. Kedua institusi ini harus merumuskan hak dan kewajiban dalam kontek pengawasan, monitoring, dan evaluasi. Dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan PHSK perlu ditetapkan kriteria dan indikator pengelolaan yang lestari seperti aspek ekonomi, ekologi dan sosial. Kriteria-kriteria tersebut harus disesuaikan dengan kondisi atau tipologi suatu daerah dan disesuaikan dengan konsep “small forest” seperti misalnya ukuran luasnya berbeda-beda.
Sertifikasi juga dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk mengetahui kinerja PHSK yang lestari. Di Jepang, Forest Stewardship Council (FSC) merupakan salah satu lembaga yang memberikan sertifikasi dalam PHSK. Beberapa perusahaan PHSK di Jepang telah menerima sertifikat lingkungan. Perusahaan ini mengelola hutan seluas 3300 ha dengan 200 pemilik yang berbeda. Selain memberikan sertifikasi bagi pengelola yang memiliki kinerja baik, monitoring juga difungsikan untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan yang dihadapi dalam PHSK.
E. Penutup
Pengelolaan hutan skala kecil memberikan alternatif baru dalam pengelolaan hutan produksi yang memberikan kesempatan kerja dan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat. Di Indonesia PHSK dapat diterapkan diantaranya dalam bentuk hutan rakyat, agroforestary dan manajemen kolaborasi antara inti - plasma. Hal ini tentunya harus diimbangi dengan aturan main yang jelas, terutama mengenai status kepemilikan dan pembagian hasil pada lahan-lahan yang dimiliki negara. Satu hal yang harus tetap dipegang adalah bahwa PHSK berbasis masyarakat ini harus digali dari kearifan tradisional yang terdapat dalam masyarakat tersebut dan tidak dapat dipaksakan sebagai suatu bentuk yang baku.***
BUDIDAYA GAHARU : Alternatif Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan
Sudah gaharu, cendana pula! Sudah tahu, bertanya pula! Peribahasa tersebut sangat sering kita dengar sehari-hari. Akan tetapi tidak banyak dari kita yang tahu apakah gaharu tersebut dan darimana ia dihasilkan. Gaharu sebenarnya merupakan substansi aromatik (aromatic resin) yang berbentuk gumpalan atau padatan berwarna coklat muda sampai kehitaman yang terbentuk pada lapisan dalam kayu tertentu. Timbulnya gaharu ini bersifat spesifik, dimana tidak semua pohon dapat menghasilkan substansi aromatik ini.
Jenis-jenis pohon yang biasanya menghasilkan gaharu adalah pohon-pohon yang termasuk famili Thymelaeaceae yakni Gonystyloidae (antara lain Gonystylus spp.), Aquilarioideae (Aquilaria spp.), Thymelaeoidae (Enklea spp, serta Wikstroemia spp.), dan Gilgiodaphnoidae. Bahkan ada ahli yang berpendapat bahwa jenis Dalbergia parvifolia (famili Leguminoceae) dan Excoccaria agolocha (Euphorbiaceae) juga dapat menghasilkan gaharu. Akan tetapi jenis yang diketahui memiliki potensi penghasil gaharu tertinggi adalah Aquilaria malaccensis atau dikenal dengan nama daerah Karas, Alim, Garu, Kompe dan lain-lain.
Penyebaran alami marga Aquilaria sangat luas mulai dari India, Pakistan, Myanmar, Thailand, Kamboja, Malaysia, Philipina dan Indonesia. Enam diantaranya ditemukan di Indonesia (A. malaccensis, A. microcarpa, A. hirta, A. beccariana, A. cumingiana dan A. filarial) yang terdapat hampir di seluruh Nusantara, kecuali Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Akan tetapi seiring dengan maraknya illegal logging dan perburuan gaharu, pohon penghasil gaharu saat ini sangat jarang ditemui di hutan bahkan telah termasuk jenis yang hampir punah oleh CITES.
HHBK Andalan
Gaharu dikenal karena memiliki aroma yang khas sehingga digunakan untuk berbagai keperluan seperti parfum, pewangi ruangan, hio, obat, dan sebagainya. Popularitas dan tingginya harga gaharu sudah dikenal lama. Saat ini, harga gaharu kualitas super dapat mencapai Rp 5 juta per kilogram, bahkan dapat mencapai US $ 10.000 per kg di tingkat pengguna akhir. Di tingkat pengumpul di Kalimantan harga gaharu dapat mencapai Rp. 600.000,- per kg.
Kontribusi gaharu terhadap perolehan devisa juga menunjukkan grafik yang terus meningkat. Menurut BPS, nilai ekspor gaharu dari Indonesia tahun 1990-1998 adalah sebesar US $ 2 juta, dan pada tahun 2000 meningkat menjadi US $ 2,2 juta. Namun sejak 2000 sampai akhir 2002, ekspor menurun menjadi 30 ton dengan nilai US $ 600.000. Penurunan ini disebabkan oleh semakin sulitnya gaharu ditemukan.
Mempertimbangkan harganya yang sangat istimewa bila dibandingkan hasil hutan lainnya, gaharu dapat dikembangkan sebagai salah satu komoditi hasil hutan bukan kayu (HHBK) andalan alternatif untuk penyumbang devisa sektor kehutanan selain dari hasil hutan kayu.
Budidaya Gaharu : Peningkatan Kelestarian Hutan
Nilai jual gaharu yang tinggi ini seharusnya dapat mendorong masyarakat untuk membudidayakannya. Selama ini gaharu yang dipanen umumnya berasal dari pohon gaharu yang tumbuh alami di hutan. Jika dahulu masih terdapat kearifan tradisional dimana untuk menjamin kelestarian pohon induknya, hanya bagian yang mengandung gaharunya saja yang ditoreh tanpa menebang pohonnya, saat ini pemanenan dilakukan dengan langsung menebang pohonnya. Akibatnya semakin sedikit pohon-pohon induk gaharu yang terdapat di alam.
Walaupun tidak seorangpun yang meragukan prospek ekonominya, sejauh ini upaya peremajaan dan budidaya gaharu belum begitu dikenal. Bukan tidak ada penelitian yang menunjukkan besarnya peluang pengembanganya, akan tetapi akibat lemahnya publikasi dan tindak lanjut terhadap hasil penelitian tersebut menyebabkan usaha pengembangan gaharu sangat jauh tertinggal dibandingkan jenis pohon lainnya, misalnya, jati emas atau jati super yang didengung-dengungkan akan memberikan nilai ekonomi yang cukup besar sehingga penanaman jenis ini mewabah di mana-mana, walaupun kemudian penanaman jenis ini tidak direkomendasikan.
Penelitian Litbang Kehutanan dan lembaga riset lainnya menunjukkan bahwa gaharu yang timbul disebabkan oleh terjadinya infeksi yang dialami pohon gaharu tersebut. Para peneliti menduga terdapat tiga hal penyebab proses infeksi, yaitu (1) infeksi jamur seperti Fusarium oxyporus, F. bulbigenium dan F. laseritium., (2) perlukaan dan (3) proses non-phatology. Terjadinya luka pada pohon dapat mendorong munculnya proses penyembuhan yang akan menghasilkan gaharu.
Penanaman dapat dilakukan pada lahan terbuka dengan sistem monokultur, tetapi lebih disarankan dibawah tegakan seperti Sengon, Petai, Gamal, dan Mahoni baik dengan sistem tumpang sari maupun campuran. Pohon gaharu umumnya dapat ditanam pada lokasi dengan ketinggian 5 – 700 mdpl dengan curah hujan 6 bulan dan sepanjang tahun lebih disukai.
Tanaman gaharu dapat dipanen setelah berumur 9-10 tahun. Setelah pohon berdiameter 10 cm (kira-kira pada umur 5 tahun), proses inokulasi dapat dilakukan dengan cara (1) melukai bagian batang pohon, (2) menyuntikkan mikroorganisme jamur Fusarium, (3) menyuntikkan oli dan gula merah, atau dengan (4) memasukan potongan gaharu ke dalam batang tanaman. Produksi gubal gaharu mulai terbentuk setelah satu bulan penyuntikan dengan tanda-tanda pohon tampak merana, dedaunan menguning dan rontok, kulit batang rapuh, jaringan kayu berwarna coklat tua dan mengeras, dan jika dibakar akan mengeluarkan aroma khas mirip kemenyan. Gaharu dapat dipanen 3 – 4 tahun kemudian.
Jumlah produksi gubal gaharu dapat beragam tergantung kualitas pohon dan tempat tumbuhnya dengan rata-rata 2 kg per pohon. Dengan jarak tanam 3 x 3 m atau 1100 pohon per ha, maka akan dihasilkan sekitar 2 ton gaharu/ha. Jika kita asumsikan bahwa gaharu yang dihasilkan hanya kualitas rendah dengan harga Rp 250 - 300 ribu per kilo maka akan diperoleh pendapatan Rp 550 - 660 juta per ha. Bagaimana jika dihasilkan tersebut gaharu kualitas super dengan harga Rp 600 ribu pada pedagang pengumpul ? Suatu jumlah yang sangat fantastis untuk usaha lebih kurang 10 tahun.
Terdapat berbagai pilihan untuk menggalakkan budidaya gaharu, antara lain melalui (1) program hutan rakyat gaharu, dan (2) program hutan kemasyarakatan. Dalam program hutan rakyat, masyarakat diharapkan secara swadaya melakukan penanaman gaharu pada lahannya sendiri terutama pada lahan kosong (tidak produktif). Agar masyarakat mau menanam gaharu, selain informasi tentang peluang dan teknik pengembangan gaharu, masyarakat juga harus diberikan insentif, seperti pengadaan bibit dan inokulasi mikroorganisme penyebab gaharu. Pengadaan bibit dan inokulasi dapat dilaksanakan oleh pemerintah yang kemudian disalurkan kepada petani secara cuma-cuma atau dengan kredit. Dalam prakteknya pengembangan hutan rakyat gaharu ini dapat dikombinasikan dengan tanaman semusim atau tahunan.
Sedangkan penggalakan program hutan kemasyarakatan didasarkan pada paradigma pembangunan kehutanan community based development yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem hutan kemasyarakatan, masyarakat diperbolehkan menanam gaharu bersama-sama dengan tanaman pertanian dan kehutanan lainnya pada lahan hutan, salah satunya dengan sistem agroforestry.
Berbagai praktek agroforestry menunjukkan bahwa sistem ini memberikan dampak ganda berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat di satu sisi dan kelestarian sumberdaya hutan dan lahan disisi lain. Selain memperoleh kesejahteraan dari tanaman gaharu dan tanaman kehutanan, masyarakat juga dapat memanfaatkan lahan diantara tanaman tersebut untuk tanaman semusim. Teknik ini memberikan pengaruh positif terhadap produktivitas tanah berupa meningkatnya ketersediaan unsur hara dan bahan organik serta menurunnya kemasaman tanah. Teknik ini juga dapat menekan laju erosi tanah sehingga juga cocok untuk menanggulangi lahan kritis.
Adanya peningkatan kesejahteraan dari budidaya gaharu ini akan mengurangi tekanan masyarakat terhadap sumber hutan dalam bentuk illegal logging dan perambahan lahan bahkan masyarakat secara sadar akan mempertahankan setiap jengkal hutan dari kerusakan, apapun penyebabnya. Tentu saja agar program penanaman gaharu ini berhasil perlu didukung dengan kelembagaan dan peraturan yang jelas, serta dukungan semua pihak. Jadi mengapa kita tidak tanam gaharu? ***
*Peneliti pada Litbang Kehutanan Sumatera
25 Juli 2008
Strategi Pengelolaan Hutan di NAD Setelah Moratorium Penebangan
Oleh : Cut Rizlani Kholibrina dan Aswandi Untuk menyelamatkan hutan yang tersisa, Gubernur NAD mengeluarkan kebijakan moratorium logging (jeda tebang) tidak lama setelah diangkat sebagai pemimpin rakyat Aceh. Kebijakan ini patut diacungi jempol karena memihak lingkungan dengan mengurangi penebangan liar sehingga mendapatkan apresiasi yang tinggi dari berbagai pihak. Apresiasi yang tinggi terhadap konsistensi kebijakan ini kembali disampaikan para wakil rakyat di DPRD NAD pada tanggal 26 Mei dalam Sidang Paripurna Pembahasan RAPBA 2008 yang juga dihadiri oleh Gubernur. Akan tetapi apresiasi yang disampaikan juga diikuti dengan pertanyaan : Apa yang harus dilakukan untuk menutupi kebutuhan kayu sedangkan hasil kayu dari hutan produksi NAD nihil dan pemenuhan dari hutan rakyat belum dapat diandalkan?. Jika pun terdapat kayu rakyat, perangkat peraturan yang ada belum menjadi insentif bagi masyarakat menanam pohon. Pertanyaan ini sangat realistis mengingat NAD membutuhkan kayu yang sangat tinggi bagi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami hingga 200.000 m3/tahun (Kompas, 7 April 2006). Apabila kebijakan jeda tebang ini tidak diikuti oleh perangkat kebijakan yang mendukung maka akan sangat sulit kebijakan pro lingkungan ini dapat bertahan dalam jangka panjang. Insentif Pengembangan Hutan Rakyat Disadari bahwa untuk menghentikan penebangan liar dibutuhkan pendekatan yang komprehensif mulai dari penegakan hukum, penataan pasar dan pemenuhan kebutuhan kayu dari alternatif usaha kehutanan yang lestari. Jika selama ini kita mengandalkan Hak Pengusahaan Hutan (Izin Usaha Pemungutan Hasil Hutan Kayu) untuk memenuhi kebutuhan kayu yang terbukti tidak lestari dan tidak memiihak masyarakat, tidak ada salahnya kita mulai menggali skim pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Tidak seperti HPH yang padat modal dan skala luas, skim ini dapat memiliki luasan yang kecil, padat karya dengan partisipasi masyarakat yang tentu berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Salah satu skim pengelolalaan hutan bersama masyararakat adalah hutan rakyat. Hutan rakyat dapat dikembangkan pada lahan milik atau lahan yang dibebani hak-hak lainnya di luar kawasan hutan dengan tujuan untuk menghasilkan kayu rakyat dan rehabilitasi lahan. Luas hutan rakyat minimal 0,25 ha dengan penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan atau jenis tanaman lainnya lebih dari 50% dan atau pada tanaman tahun pertama dengan tanaman minimal 500 tanaman per-hektar. Sesungguhnya hutan rakyat telah lama berkembang di masyarakat dan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagai investasi dan penghasilan tambahan yang dapat diandalkan. Hal inilah yang mendorong pemerintah memberikan berbagai insentif seperti Kredit Usaha Hutan Rakyat (KUHR) sejak tahun 1997 dan mengeluarkan berbagai peraturan penertiban kayu rakyat. Tetapi dalam pelaksanaannya, kebijakan yang dikeluarkan malah menjadi disinsetif. Kewajiban kayu hutan rakyat memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) menambah beban biaya. Padahal, dalam PP 34/2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan disebutkan bahwa kayu yang berasal dari hutan hak diberi Surat Keterangan Asal Usul yang diterbitkan oleh kepala desa atau pejabat setara dan berlaku sebagai SKSHH. Untuk memperkuat PP tersebut dikeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.51/Menhut/II/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Penggunaan SKAU untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak. Tetapi perbedaan penafsiran dari berbagai stakeholder mengakibatkan insentif ini tidak berjalan dengan baik. Adanya over-acting oknum keamanan dalam penertiban kayu juga sedikit banyak meruntuhkan semangat petani hutan rakyat. Belum lagi beberapa kewajiban lainnya seperti retribusi daerah, jasa keamanan dan lainnya yang mengakibatkan biaya tinggi sehingga masyarakat tidak tertarik menanam karena kesulitan memanennya. Tidak ada jalan lain yang harus ditempuh pemerintah daerah NAD selain memberikan insentif kebijakan yang tepat dan betul-betul berpihak. Peluang otonomi daerah yang memberikan kewenangan daerah untuk menyusun perangkat hukum dan birokrasi yang lebih ringkas harus dimanfaatkan. UUPA dan Qanun Kehutanan NAD harus diberdayakan dan diperkuat dengan penyusunan perangkat hukum dibawahnya. Banyaknya hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perundangan kehutanan (UU, PP dan SK Menteri) tidak boleh dijadikan penghambat. Harus mulai diinisiasikan pembelajaran masyarakat dapat penyusunan Peraturan Desa terutama yang berkaitan dengan penguatan bukti-bukti atau asal usul kayu rakyat. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang berada di luar kawasan hutan seperti rotan, getah damar, lebah madu dan lainnya yang belum memiliki payung hukum dapat difasilitasi dengan penerbitan qanun (perda) yang berkaitan dengan hal tersebut. Insentif pengembangan hutan rakyat juga dapat diberikan melalui pembebasan biaya dan kemudahan birokrasi dalam pengurusan izin/ surat keterangan, kredit lunak, penghapusan berbagai pungutan/ retribusi, bantuan pembangunan dan pemeliharaan hutan rakyat dan sebagainya yang tentu saja akan lebih mudah pelaksanaannya dalam kerangka otonomi daerah. Koordinasi antar sektor (Kehutanan, Perhubungan, Koperasi, Perdagangan, dan Kepolisian) harus dilakukan sehingga keragaman interpretasi terhadap suatu kebijakan dapat dihindari. Jasa Lingkungan : Carbon Trade Perhatian dunia terhadap pemanasan global mengemuka dalam dua dasa warsa terakhir dan puncaknya pada Konvensi Internasional tentang Perubahan Iklim yang dikenal dengan Protokol Kyoto. Dalam protocol tersebut disepakati bahwa pemanasan global merupakan masalah semua bangsa sehingga penanganannya harus melibatkan semua negara. Dalam protocol tersebut ditawarkan beberapa solusi seperti mekanisme pembangunan bersih (Clean Development Mechanism) dan pencegahan deforestasi (Avoided Deforestation/AD) yang mengacu pada pencegahan hilangnya hutan untuk menurunkan emisi gas yang akan mengakibatkan pemanasan global. Ide dasar mekanisme ini adalah negara-negara maju di Utara membayar negara-negara berkembang di selatan untuk mengurangi penggundulan hutan dengan memberi bantuan keuangan untuk kepentingan tersebut. Dalam perkembangannya mekanisme AD tidak hanya saja mengusung pencegahan deforestasi, tetapi juga penurunan emisi dari pencegahan degradasi hutan. Skim ini kemudian dikenal sebagai Reduced Emission from Degradation and Deforestations (REDD). REDD menawarkan kewajiban membayar melalui sistem perdagangan karbon bagi negara-negara maju kepada negara-negara berkembang guna mengurangi penggundulan hutannya. Skim REDD ini menjanjikan kempensasi dana hingga US$3,75 miliar (Rp33,75 triliun) pertahun dari negara-negara maju untuk menyelesaikan masalah kerusakan hutan. Mekanisme yang ditawarkan oleh REDD dapat menjadi sumber pendapatan pemerintah (pusat/ daerah) dengan adanya dana kompensasi tersebut, terutama dalam kerangka otonomi khusus – dalam pengelolaan hutan. Dana kompensasi juga dapat diberikan kepada pengelola kawasan lindung, inisiatif pemberantasan illegal logging, skema pembayaran jasa lingkungan dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Dengan kondisi kawasan lindung yang mendominasi fungsi lahan di NAD, telah adanya inisiatif pemberantasan illegal logging melalui moratorium penebangan, skim REDD ini dapat dijadikan peluang untuk memperoleh dana kompensasi yang dapat dijadikan sumber pembiayaan pengelolaan dan perlindungan hutan di NAD. Apakah sudah ada pemerintah daerah yang memulai? Pemerintah Daerah Papua menyatakan kesiapannya menjadi daerah percontohan kegiatan REDD mulai pertengahan 2008 (Kompas, 6/12/2007). Akan tetapi satu hal yang harus disiapkan oleh stakeholder kehutanan NAD, bahwa apapun strategi yang akan ditempuh masalah penatagunaan dan pengukuhan hutan merupakan hal pertama yang harus diselesaikan. |
23 Juli 2008
Memanen Hutan Tanpa Menebang Kayu
Pada bulan Desember 2007 Indonesia akan menjadi tuan rumah Konferensi Internasional Perubahan Iklim Ke-13 di Bali. Selain akan membahas isu-isu penting seperti pemanasan global juga akan dibahas rencana aksi dan penguatan tekad semua pihak untuk menciptakan pengelolaan lingkungan hidup global yang lebih baik. Tetapi, seberapa pentingkah pertemuan ini bagi Indonesia? Sebagai negara tropis dengan kawasan hutan yang sangat luas (baik yang masih berhutan ataupun telah gundul), Indonesia memiliki peran penting bagi pengaturan iklim dunia. Mengapa? Hal ini dikarenakan hutan sangat berperan dalam siklus karbon, unsur/senyawa yang bersama-sama dengan gas rumah kaca lainnya, memberi andil terjadinya pemanasan global. Peningkatan suhu bumi sebesar 1,4 - 5,8°C dalam beberapa dasawarsa terakhir memiliki hubungan erat dengan peningkatan emisi karbon di atmosfer akibat limbah industri dan rusaknya ekosistem hutan. Dampak dari peningkatan suhu bumi saat ini bukan tidak terasa. Perubahan iklim telah mengakibatkan musim kering berlangsung lebih lama dan kering, musim hujan berlangsung lebih singkat dengan pola tidak menentu yang menyebabkan banjir dan tanah longsor. Fluktuasi suhu juga memicu wabah berbagai jenis penyakit seperti flu dan malaria, dan berbagai penyakit baru yang muncul dan menyebar dengan cepat. Di Kutub Utara, lapisan es mencair sehingga meningkatkan permukaan air laut 15 - 95 cm di Greenland. Bagian terbesar pertukaran karbon (CO2 dan CO) antara atmosfer dan daratan terjadi di hutan karena vegetasi hutan menyerap karbon melalui fotosintesis untuk membangun biomassa kayu yang setengahnya merupakan senyawa karbon. Dengan demikian status pengelolaan hutan akan menentukan apakah daratan bertindak sebagai sumber emisi (source) atau rosot (sink) karbon. Walaupun di satu sisi hutan dapat menyerap karbon atmosfer dalam jumlah yang besar, tetapi aktivitas manusia terhadap hutan dapat menyebabkan terjadinya peningkatan emisi gas rumah kaca terutama CO2 ke atmosfer. Konversi hutan menjadi areal pekebunan dan peruntukan lainnya, penebangan hutan (legal dan ilegal), serta kesalahan pengelolaan hutan lainnya diperkirakan memberikan kontribusi sekitar 30 % total emisi karbon ke atmosfer setiap tahunnya. Peran hutan sebagai rosot (pengurangan) karbon di atmosfer mendapat perhatian serius dunia setelah penandatanganan Protokol Kyoto pada United Nations Framework Convention on Climate Change tahun 1997. Beberapa provisi protokol tersebut dapat mempengaruhi praktek pengelolaan hutan di negara berkembang, seperti Artikel 3.3 yang memberikan peluang pemanfaatan jasa lingkungan rosot karbon melalui kegiatan pengelolaan hutan lestari di negara lain untuk memenuhi target penurunan emisi karbon negara-negara industri. Artikel lain juga menetapkan mekanisme perdanaan melalui kredit karbon bagi proyek-proyek kehutanan yang meningkatkan penyimpanan karbon. Karena negara-negara industri umumnya memiliki lahan terbatas untuk pembangunan hutan baru dan penurunan emisi secara mekanis sangat terkait dengan teknologi baru yang mahal, maka kewajiban untuk memenuhi target penurunan emisi tersebut dapat dilakukan dengan membangun hutan di negara lain. Mekanisme ini (Clean Development Mechanism--CDM) memungkinkan negara-negara berkembang memperoleh dana bagi kegiatan pengelolaan hutannya. Hal ini akan memberikan implikasi positif bagi pengelolaan hutan lestari dimana pengelola hutan yang dapat mendokumenkan peningkatan penyimpanan karbon dari kegiatan pengelolaannya seperti penanaman, rehabilitasi dan perlindungan dan konservasi dapat memperoleh kesempatan penjualan kredit karbon. Penanaman dan Konservasi Praktek pengelolaan hutan dapat digunakan untuk mengurangi akumulasi gas rumah kaca melalui dua pendekatan, yaitu (1) aktivitas yang dapat meningkatkan jumlah dan laju akumulasi karbon pada produk kehutanan (pohon dan produk kayu) dan (2) aktivitas yang dapat mengurangi laju pelepasan karbon yang telah difiksasi (hasil fotosintesis) vegetasi hutan ke atmosfer. Aktivitas pendekatan pertama adalah berupa penanaman pohon, sedangkan pendekatan kedua dapat berupa kegiatan konservasi hutan dan pengelolaan hutan dengan dampak minimal. Salah contoh proyek fiksasi karbon yang dapat dijadikan contoh perdagangan kredit karbon adalah kegiatan penanaman pengkayaan dan rehabilitasi hutan bekas tebang pilih seluas 25.000 ha di Sabah, Malaysia. Proyek tersebut yang didanai oleh perusahaan listrik Belanda sebesar US$ 15 juta (US$ 3,52/ton karbon) selama 25 tahun untuk offset (penyeimbang) emisi kegiatan industri perusahaan tersebut. Penanaman pohon ini mampu menyimpan 4,3 juta ton karbon, dan menghasilkan hasil kayu senilai US$ 800 juta yang dikembalikan untuk program pembangunan masyarakat desa hutan. Konservasi hutan memainkan peran ganda dalam hubungannya sebagai rosot karbon. Pertama, skim ini melindungi dan mencegah emisi karbon yang diakibatkan oleh dekomposisi biomassa hutan dan kedua, dengan menjaga penutupan hutan maka akan berkurang pengaruh pemanasan global. Salah contoh kegiatan konservasi hutan yang dimanfaatkan sebagai offset karbon adalah proyek konservasi hutan di Belize seluas 87.000 ha pada hutan lindung tropis dan lahan terdegradasi. Proyek ini didanai konsorsium perusahaan listrik Amerika Serikat sebesar US$ 2,6 juta (US$ 1,90/ton karbon). Selain menyimpan 1,3 juta ton karbon berupa vegetasi hutan, kegiatan ini memberikan efek positif terhadap keanekaragaman hayati, stabilitas tanah, kualitas air dan udara, menciptakan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi lokal melalui pengembangan industri hasil hutan non kayu. Kegiatan lain yang dapat dimanfaatkan sebagai offset karbon adalah kegiatan pengelolaan hutan yang dapat menghindari atau mengurangi emisi karbon akibat kegiatan penebangan dan kerusakan yang ditimbulkannya. Salah satu contohnya adalah proyek penebangan hutan yang meminimalkan dampak kerusakan di Malaysia yang bertujuan untuk menurunkan dampak kerusakan tebang pilih seluas 10.400 ha. Proyek ini didanai oleh Innoprise Corporation dan New England Power, perusahaan listrik Amerika sebesar US$ 3 juta selama 8 tahun (atau US$ 7,6/ton karbon). Proyek ini mencegah emisi 58.000 ton karbon dan kerusakan 10.400 ha area hutan tropis. Alternatif Pengelolaan Hutan Disadari bersama bahwa pilihan skim pengelolaan hutan sangat menentukan lestari tidaknya hutan yang dikelola. Orientasi pengelolaan hutan yang hanya terfokus pada hasil kayu telah mengakibatkan kerugian yang luas biasa baik secara ekonomi maupun ekologi. Orientasi ekonomi jangka pendek ini pulalah yang mengakibatkan rusaknya ekosistem hutan. Kerusakan hutan tersebut mengakitkan bencana lonsor dan banjir yang menelan korban jiwa dan material yang tidak sedikit. Dengan kondisi kawasan lindung yang mendominasi fungsi lahan di NAD, pengelolaan hutan harus diarahkan pada kegiatan perlindungan dan konservasi hutan serta rehabilitasi lahan kritis. Mekanisme CDM melalui penjualan jasa karbon dari kegiatan konservasi dan rehabilitasi hutan dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan pengelolaan hutan dan pembangunan daerah. Selain menyerap karbon, kegiatan ini juga memberikan efek positif terhadap keanekaragaman hayati, stabilitas tanah, kualitas air dan udara, menciptakan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi lokal melalui pelibatan aktif masyarakat dalam pengembangan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan seperti ekowisata. Skim ini juga dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pengelolaan hutan lestari di NAD karena sangat sejalan dengan keinginan politis pemerintah daerah untuk menghentikan penebangan hutan (legal maupun ilegal), konversi hutan dan meningkatkan kinerja pelestarian Kawasan Ekosistem Leuser. Jadi daripada kita menebang dan menjarah hutan hanya untuk beberapa puluh dolar yang hanya dinikmati segelintir oknum dan kita menderita akibat bencana banjir, longsor dan kekeringan yang diakibatkannya serta kehilangan penghasilan sebesar 7 Milyar dolar dalam 15 tahun mendatang, mengapa kita tidak mulai melirik peluang ini sebagai bagian dari kegiatan pengelolaan hutan lestari?. Oleh : Cut Rizlani Kholibrina Telah dipublikasikan pada Harian Serambi Indonesia |
17 Juli 2008
Rehabilitasi Lahan Kritis dengan Agroforestry
Berbagai cara untuk menangani lahan kritis ini telah dilakukan oleh pemerintah bahkan sejak lama, yakni tahun 1976 antara lain melalui program reboisasi dan penghijauan. Akan tetapi keberhasilan fisik dari kegiatan reboisasi dan penghijauan tersebut relatif rendah yakni sekitar 68% dan 21 %. Dalam lingkup Sumatera Utara, realisasi kegiatan rehabilitasi lahan ini juga relatif rendah dimana dari 3.766 ha lahan kritis dalam kawasan hutan hanya 1.279 ha yang terealisasi, serta 16.033 ha yang terealisasi dari 22.711 ha yang direncanakan pada lahan kritis di luar kawasan hutan (Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, 2002). Hal ini disebabkan karena kurang tepatnya teknologi yang diterapkan, kondisi lahan belum dipelajari dengan cermat, serta kesenjangan antara kepedulian masyarakat dan pemerintah terhadap masalah ini dengan tindakan nyata yang komprehensif untuk mengatasinya dimana terdapat kecenderungan kegiatan ini hanya terbatas pada aspek teknis dan dikerjakan dalam kerangka keproyekan saja.
Upaya pemerintah untuk mengatasi degradasi lingkungan melalui gerakan nasional rehabilitasi lahan (GNRHL) juga mendapat kritikan keras dari berbagai kalangan. Gerakan itu dinilai hanya menghambur-hamburkan anggaran, apalagi pemerintah hingga kini belum menemukan satu pedoman pelaksanaan yang efektif. Sangat disayangkan jika gerakan nasional yang membutuhkan dana trilyunan rupiah itu tidak dilaksanakan dengan perencanaan yang matang.
Permasalahan Lahan Kritis
Walaupun pemerintah telah mengeluarkan SK Menhut No. 20/Kpts-II/2001, tentang standar dan kriteria rehabilitasi hutan dan lahan yang merupakan acuan dari seluruh pihak untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan secara terpadu dan berkelanjutan, hingga saat ini masih banyak lahan-lahan kritis yang belum mendapat perhatian untuk direhabilitasi menjadi produktif kembali.
Ciri-ciri utama lahan kritis adalah lahan yang gundul, berkesan gersang, dan bahkan muncul batu-batuan di permukaan tanah, topografi lahan pada umumnya berbukit atau berlereng curam. Selain itu lahan kritis juga memiliki tingkat produktivitasnya rendah dan vegetasi alang-alang yang mendominasinya dengan sifat-sifat lahan yang memiliki pH tanah relatif rendah.
Meluasnya lahan kritis tidak dapat dilepaskan dari beberapa hal, antara lain (i) tekanan penduduk yang tinggi akan lahan, (ii) perladangan berpindah, (iii) padang penggembalaan yang berlebihan, (iv) pengelolaan hutan yang tidak baik, dan (v) pembakaran yang tidak terkendali. Fujisaka dan Carrity (1989) mengemukakan bahwa masalah utama yang dihadapi di lahan kritis antara lain adalah lahan mudah tererosi, tanah bereaksi masam dan miskin unsur hara.
Agroforestry dan Usaha Tani Konservasi
Masalah mendasar yang dihadapi pada lahan kritis adalah bagaimana mengubah lahan tersebut menjadi produktif kembali dan bagaimana menghambat agar lahan kritis tidak semakin meluas. Penanganan masalah lahan kritis secara parsial yang telah ditempuh selama ini ternyata tidak mampu mengatasi masalah yang kompleks ini. Oleh karena itu strategi penanganan lahan kritis perlu diubah melalui pendekatan holistik dengan fokus sumberdaya berbasiskan masyarakat. Dalam hal ini, upaya peningkatan produktivitas lahan kritis hanya akan dapat berhasil apabila masyarakat dilibatkan sebagai aktor utama serta mereka memperoleh peningkatan kesejahteraan dari kegiatan rehabilitasi lahan tersebut. Diantara kegiatan rehabilitasi berdasarkan pendekatan ini adalah agroforestry dan sistem usaha tani konservasi.
Walaupun sistem agroforestry (wanatani) banyak ragamnya, satu hal yang sama adalah bahawa penanaman pohon dilakukan bersamaan dengan berbagai jenis tanaman pertanian. Agar keberhasilan sistem ini tinggi, kombinasi jenis serta pola tanaman harus lestari secara ekologi dan ekonomi sehingga pemasaran hasil tanaman pertanian harus dianalisa secara cermat dan teliti. Pasar kayu (pulp) lokal dan industri juga dikaji secara seksama karena faktor ini menetukan kelayakan penanaman pohonnya. Yang terpenting adalah bahwa sistem agroforestry merupakan sistem yang permanen dan lestari sehingga hak atas lahan untuk jangka panjang harus jelas karena sistem ini mempunyai rotasi yang lama.
Hampir serupa dengan agroforestry usaha tani konservasi diatur melalui pengaturan pola tanam, penambahan bahan organik dengan daur ulang sisa panen dan gulma, serta penerapan budidaya lorong. Penerapan teknik ini akan memberikan pengaruh positif terhadap produktivitas tanah berupa meningkatnya ketersediaan unsur hara dan bahan organik tanah serta menurunnya kemasaman tanah. Teknik ini juga dapat menekan laju erosi tanah, serta mengurangi biaya pembuatan teras dan galengan.
Salah satu contoh usaha tani konservasi dengan budidaya lorong adalah penanaman rumput raja atau rumput gajah sebagai tanaman pagar dan rotasi jagung-kedelai atau jagung-jagung sebagai tanaman lorong bersama-sama dengan tanaman kehutanan. Rumput raja selain sebagai pupuk hijau juga dapat menekan laju erosi. Sistem ini juga merupakan tindakan konservasi vegetatif yang baik karena dapat menutupi permukaan tanah sepanjang tahun. Menjadi lebih baik lagi jika sisa tanaman juga dikembalikan sebagai tambahan bahan organik tanah. Bahan organik yang tinggi tidak hanya akan menambah nutrisi tanah, tetapi juga dapat berperan sebagai pengikat air dan meningkatkan daya infiltrasi tanah, mengurangi erosi dan aliran permukaan pada saat hujan turun.
Untuk mengatasi invasi alang-alang, setelah dibajak, areal harus dinaungi dengan jenis tanaman cepat tumbuh yang cepat membentuk tajuk tertutup. Setelah beberapa tahun, tegakan dapat dijarangi dan jenis-jenis yang toleran terhadap naungan seperti kopi atau bahkan lada dapat ditanam. Pohon-pohon naungan tersebut dapat dimanfaatkan kayunya kayu bakar atau untuk pulp.
Pemilihan jenis tanaman juga sangat menentukan keberhasilan kegiatan rehabilitasi lahan kritis. Dalam hal ini perlu dicari tanaman yang mampu beradaptasi terhadap keadaan lingkungan yang memiliki kesuburan yang rendah dan ketersediaan air terbatas. Tanaman tesebut juga harus bisa tumbuh cepat sehingga bisa menutup tanah dalam waktu yang tidak lama, memiliki resistensi yang tinggi terhadap kebakaran serta mampu berproduksi secara optimal sehingga dapat diharapkan sebagai sumber pendapatan di masa mendatang. Berdasarkan percobaan Litbang Kehutanan di Tapanuli Selatan, salah satu contoh jenis pohon yang mampu bertahan pada kondisi ini adalah Acacia crassicarpa.
Karena penanganan tanah kritis tersebut berhubungan erat dengan masalah kemiskinan penduduknya, tingginya kepadatan populasi, kecilnya luas lahan, kesempatan kerja terbatas dan lingkungan yang terdegradasi, maka kajian kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat (building capacity) sangat diperlukan untuk keberhasilan kegiatan rehabilitasi ini***
Aswandi
Peneliti pada Balai Penelitian Kehutanan Aek Nauli